SuaraParlemen.co, Jakarta – Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih dikenal dengan R.A Kartini, merupakan simbol perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Namanya terus dikenang karena tekad dan semangatnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah tradisi dan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan.
Masa Kecil Kartini: Tumbuh di Tengah Tradisi
Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari pasangan Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan M.A Ngasirah. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan Jawa yang masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat.
Meskipun lahir sebagai perempuan di masa yang membatasi pendidikan bagi kaumnya, Kartini tidak menyerah. Ia haus ilmu dan memiliki pemikiran yang lebih maju dibanding perempuan lain pada zamannya. Semangatnya belajar dan keterbukaannya terhadap ide-ide baru menjadi fondasi awal perjuangannya kelak.
Kisah Cinta yang Terlupakan
Banyak orang mengenal perjuangan Kartini, namun hanya sedikit yang mengetahui kisah cintanya yang menyayat hati. Dalam buku R.A Kartini karya Imron Rosyadi, diceritakan bahwa pada tahun 1875, ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ayu Muryam, keturunan Raja Madura, demi menjaga status kebangsawanannya. Dari pernikahan ini, lahirlah saudara tiri Kartini, yaitu Roekmini dan Kardinah.
Pada tahun 1903, Kartini berhasil mewujudkan mimpinya mendirikan sekolah bagi perempuan di Jepara. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Di tahun yang sama, datang lamaran dari Bupati Rembang, Djojo Adiningrat—seorang duda dengan tujuh anak dan dua istri (selir). Salah satu syarat dari pihak Bupati adalah Kartini menjadi pengganti istri pertamanya yang telah wafat.
Kartini yang saat itu melihat kondisi ayahnya kian memburuk, merasa tak punya pilihan. Demi membahagiakan sang ayah, ia menerima lamaran tersebut—meski hatinya sendiri remuk.
“Saya kini adalah tunangan Bupati Rembang, seorang duda dengan tujuh anak dan dua istri (selir). Mahkota saya sudah lenyap dari dahi saya,” tulis Kartini dalam surat tertanggal 10 dan 14 Juli 1903.
“Saya seperti ribuan perempuan lain yang hendak saya tolong, tetapi yang (ternyata) jumlahnya hanya saya tambah saja,” lanjutnya dengan getir.
Menikah dengan Syarat Emansipasi
Pernikahan Kartini dilangsungkan pada 8 November 1903 dengan prosesi yang sangat sederhana. Ia menolak mengenakan baju pengantin, hanya memakai untaian bunga melati. Bahkan, ia juga tidak bersedia mencium kaki suaminya—sebuah bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki saat itu.
Sebelum menikah, Kartini mengajukan dua syarat kepada Bupati Rembang: ia harus tetap diizinkan membuka sekolah dan tetap boleh mengajar. Kedua permintaan ini disetujui sang suami.
Setelah menikah, Kartini tinggal di Rembang bersama suami, dua istri lainnya, dan tujuh anak tiri. Meskipun kehidupannya diwarnai cinta kepada anak-anak tirinya, masa ini dianggap sebagai masa “kemunduran” bagi Kartini, karena semangat perjuangannya tak lagi sekuat dahulu. Surat-suratnya lebih banyak diisi pujian kepada sang suami dan kisah sederhana kehidupan rumah tangganya.
Akhir Hayat Sang Pahlawan
Kebahagiaan Kartini seolah hadir kembali saat ia mengandung anak pertamanya. Dalam surat-suratnya, ia menulis tentang rencana menyiapkan sudut khusus untuk sang bayi, bahkan mempersiapkan tempat tidur agar ia tetap bisa mengajar.
Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak laki-laki bernama Raden Mas Soesalit. Empat hari kemudian, dokter Belanda, van Ravesteyn, memeriksa kondisi Kartini dan menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat.
Namun, tak lama setelah sang dokter pergi, Kartini tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Dokter segera dipanggil kembali, tetapi keadaannya memburuk dengan cepat. Dalam waktu setengah jam, nyawa Kartini tidak tertolong.
Kematian mendadak Kartini menimbulkan berbagai spekulasi—dari racun, guna-guna, hingga pembunuhan. Namun keluarga memilih untuk tidak menggali lebih jauh dan menyatakan bahwa Kartini meninggal karena komplikasi pasca melahirkan.
Kartini telah tiada, namun semangatnya abadi. Lewat pemikiran, surat-surat, dan perjuangannya, Kartini telah membuka jalan bagi jutaan perempuan Indonesia untuk berani bermimpi dan melawan batasan. Setiap tanggal 21 April, kita mengenang bukan hanya seorang tokoh sejarah, tapi juga seorang perempuan yang berani melawan zaman demi masa depan kaumnya. (Amelia)

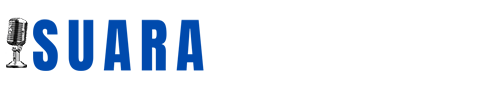





Tinggalkan Balasan