SuaraParlemen.co, Jakarta – Seorang pemilik restoran di kawasan permukiman padat Tangerang Selatan mengungkapkan adanya praktik pungutan bulanan yang dibebankan oleh sejumlah pihak di lingkungan sekitarnya.
Pelaku usaha yang enggan disebut namanya itu mengaku telah diminta menyetor uang sebesar Rp3 juta per bulan sejak pertama kali membuka usahanya pada tahun 2020.
Pungutan tersebut, kata dia, tidak hanya datang dari satu pihak, melainkan dari kelompok yang terdiri atas pemuda lingkungan, karang taruna, RT, RW, hingga tokoh masyarakat. Mereka biasanya datang secara berkelompok dan meminta uang dengan dalih “kontribusi masyarakat”.
“Dulu mereka datang rombongan. Intinya ya minta storan, katanya untuk masyarakat sini, tapi yang terima tetap dari pihak-pihak seperti ormas, RT, RW, karang taruna,” ujarnya kepada SuaraParlemen.co, Jumat (25/4).
Pada awalnya, sang pemilik restoran menolak permintaan tersebut karena menilai tidak ada dasar hukum yang jelas antara usahanya dan pihak-pihak yang meminta pungutan. Namun, penolakan itu malah berujung pada intimidasi, tekanan sosial, hingga ancaman penutupan restoran.
“Waktu saya belum setuju setor, situasinya panas. Restoran saya sering didatangi, diganggu, bahkan ada yang mabuk datang. Sampai saya pernah dipanggil ke kelurahan karena katanya usaha saya menimbulkan masalah sosial,” tuturnya.
Situasi mulai mereda setelah ia bertemu dengan seorang tokoh masyarakat yang menjadi perantara. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan: ia bersedia membayar kontribusi bulanan dengan dua syarat utama.
Pertama, ia menolak menerima proposal sumbangan dalam bentuk apapun dari siapapun. Kedua, apabila terjadi masalah sosial atau gangguan terhadap usahanya, pihak kelompok yang menerima pungutan wajib bertanggung jawab dan menyelesaikannya.
“Kalau saya bayar tiap bulan, ya jangan diganggu lagi. Saya juga bilang kalau ada masalah, saya lempar ke mereka, karena saya sudah bayar. Dan sampai sekarang, ya relatif aman. Mereka jaga juga,” katanya.
Selama hampir lima tahun menjalankan usahanya, ia memperkirakan telah menyetor sekitar Rp180 juta. Menurutnya, uang tersebut didistribusikan ke berbagai pihak di lingkungan, meski penggunaannya tidak selalu transparan.
“Saya anggap saja itu semacam pajak informal untuk bisa usaha di tengah masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengaku sebenarnya menolak praktik semacam ini karena dinilai mendekati bentuk premanisme terselubung. Namun, mempertimbangkan stabilitas usaha dan keamanan pribadi, ia memilih jalan damai dibanding melibatkan aparat atau meminta “backup” dari luar.
“Banyak yang saranin saya minta bantuan polisi atau tentara, tapi kan akhirnya saya juga mesti bayar mereka. Sama saja. Mending saya hadapi sendiri dan jaga hubungan baik dengan warga,” ujarnya.
Ke depan, ia berharap dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang tanpa tekanan pungutan semacam itu. Ia juga menginginkan peran masyarakat sekitar menjadi lebih profesional dalam mendukung pelaku usaha.
“Kalau bisa, kontribusi warga ke usaha saya itu bentuknya nyata. Bantu pasok bahan, jaga keamanan, bukan minta setoran tiap bulan,” pungkasnya. (Amelia)

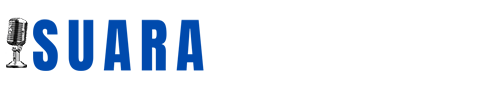




Tinggalkan Balasan